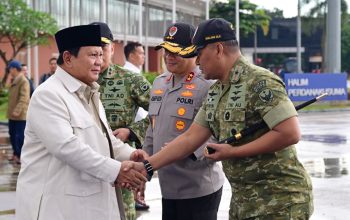RAGAM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Senin (09/02/2026) tahun ini dirayakan dalam atmosfer yang berbeda.
Di tengah hiruk-pikuk Konvensi Nasional Media Massa di Banten, industri pers Indonesia tidak lagi hanya berjuang melawan tekanan politik atau kekerasan fisik, melainkan menghadapi gelombang disrupsi teknologi bernama Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).
Meskipun teknologi informasi berkembang pesat, struktur pers nasional justru dinilai semakin rapuh.
“Kabut ketidakpastian” kini menyelimuti ruang redaksi, di mana algoritma mesin mulai mendikte distribusi informasi, menggerus pendapatan iklan, hingga menantang eksistensi jurnalis manusia.
Di tengah gempuran otomatisasi, peran jurnalis manusia justru menjadi semakin krusial dan tak tergantikan.
Fenomena ini tercermin jelas dari kasus kematian Affan yang memicu protes besar.
Ketika diminta menjelaskan insiden tersebut, chatbot AI menyimpulkan peristiwa itu sebagai kecelakaan tak disengaja dengan menggunakan imbuhan “ter-” (tertabrak), berbeda jauh dengan temuan lapangan dan persepsi publik yang melihat adanya unsur kesengajaan oleh aparat.
Kegagalan AI dalam menentukan kebenaran epistemik ini menjadi peringatan keras.
AI mungkin mampu menyintesis data dalam hitungan detik, namun ia tidak memiliki penilaian moral, empati, atau kemampuan verifikasi lapangan yang dimiliki seorang jurnalis.
“Mesin bisa memproduksi konten, tapi tidak bisa memproduksi kebenaran kontekstual. Di sinilah jurnalis berperan sebagai clearing house atau penjernih informasi di tengah banjir hoaks dan konten sintetis,” ungkap salah satu pembicara dalam konvensi tersebut.
Jurnalisme berkualitas menjadi vaksin bagi “halusinasi” teknologi yang kerap bias dan ahistoris.
Tantangan ekonomi menjadi sorotan tajam Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa perusahaan pengembang AI wajib membayar royalti atas karya jurnalistik yang mereka ambil untuk melatih mesin pintar mereka.
Praktik data scraping (penyedotan data) tanpa izin dinilai sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan media.
“Jurnalis lelah membuat berita dengan riset mendalam, tapi tiba-tiba disedot AI tanpa royalti. Jika tidak bayar, ini namanya perampokan,” tegas Komaruddin di sela-sela acara di Serang, Minggu (08/02/2026), dikutip dari Voi.
Ketimpangan ini semakin nyata ketika melihat data penurunan trafik situs berita yang signifikan akibat fitur AI Overviews di mesin pencari, yang membuat pembaca tidak lagi perlu mengklik tautan berita asli.
Ironisnya, tuntutan agar jurnalis menjadi “penjaga kebenaran” yang tangguh berbanding terbalik dengan kesejahteraan mereka.
Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam “Potret Jurnalis Indonesia 2025” menyingkap fakta bahwa 34,2 persen jurnalis masih digaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sebanyak 61,7 persen jurnalis mengalami stagnasi gaji dalam setahun terakhir, padahal beban kerja mereka meningkat drastis.
Jurnalis kini dituntut multitafsir: menulis, memotret, merekam video, hingga mengelola media sosial.
Tak jarang, tembok api (firewall) antara redaksi dan bisnis diruntuhkan demi efisiensi, memaksa jurnalis merangkap sebagai pencari iklan.
Kondisi ini diperparah dengan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menelan 922 pekerjaan media sepanjang 2024-2025.
Tanpa serikat pekerja yang kuat, jurnalis berdiri sebagai individu yang rentan di hadapan korporasi.
Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, merespons tantangan ini dengan menerbitkan regulasi baru, termasuk PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang perlindungan anak di ranah digital dan UU Pelindungan Data Pribadi.
“Kami membutuhkan dukungan media sebagai edukator dan penguat etika digital. Pers yang sehat akan melahirkan publik cerdas, yang pada akhirnya memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa,” ujar Meutya.
Peringatan HPN 2026 ini menjadi momentum refleksi bahwa meskipun AI menawarkan efisiensi, ia membawa ancaman disinformasi dan deepfake yang serius.
Oleh karena itu, keberadaan jurnalis profesional yang bekerja dengan kode etik, memverifikasi fakta, dan berpihak pada kepentingan publik, adalah kebutuhan mutlak demokrasi yang tidak bisa diotomatisasi.